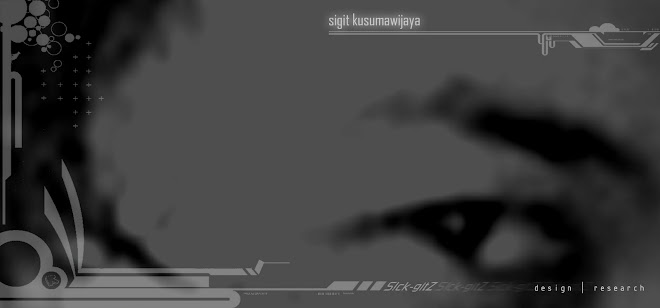This writing is a review for a journey of Yogyakarta and Solo in 2006. With his colleagues: Rafael, Arko, Bayu, Gita, Novy, Riska, Novie and Sietze Meijer, Sigit had an excursion in some gorgeous architecture spot. Nilai Keserdehanaan dan Kejujuran Sebuah Desainby: Sigit Kusumawijaya“jalinan kata terkadang belum mampu mewakilkan perasaan dan pengalaman yang dialami secara langsung”
Tulisan ini saya buat sebagai catatan perjalanan saya dan beberapa orang teman (yaitu dari Jakarta: Rafael, Arko, dan Bayu, arsitek muda yang bekerja di PT. Han Awal & Partners, Gita dan Novy, 2 orang penulis muda tentang arsitektur yang bekerja dengan Imelda Akmal, Riska dan Novie, lulusan arsitektur UPH dan seorang teman dari TU Delft Belanda, Sietze Meijer yang sedang magang di PT. Han Awal & Partners juga, teman dari Yogyakarta: Hari, dosen muda arsitektur UGM dan Eby, mahasiswa arsitektur Universitas Duta Wacana angkatan 2001, dan terakhir dari Solo: Andhika dan Galuh, lulusan arsitektur UNS, serta Tiwi, mahasiswa arsitektur UNS angkatan 2004) ketika melakukan perjalanan selama 5 hari ke daerah Yogyakarta dan Solo beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 24-28 Mei 2006. Tulisan ini hanya sekedar membagi apa yang telah kami rasakan dan alami selama perjalanan dan bagaimana kami dapat menemukan sebuah pengalaman dan pelajaran yang berharga tentang desain.
Dengan menggunakan transportasi dan akomodasi yang seadanya (pas-pasan) karena setengah backpacking setengah refreshing (kereta Bisnis, mobil sewaan dan meminjam mobil kawan, menumpang rumah kawan dan Guest House) dan diselingi pengalaman yang mengesankan karena sempat merasakan gempa pada hari Sabtunya (beruntung kami sedang berada di Solo ketika itu, namun cukup besar juga getaran yang dirasakan dari Solo) kami mendapatkan sebuah pelajaran tentang nilai kesederhanaan dan kejujuran dari sebuah desain.

Butet's House and Butet & Jaduk's Studio design by Eko Prawoto
Dengan jadwal yang cukup padat tiap harinya, kami menghabiskan perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat seperti di daerah Yogyakarta: tempat retreat dan perziarahan Sendang Sono karya Romomangun di daerah Muntilan, melewati Candi Borobudur dari jaman dinasti Syailendra karya Gunadharma di abad ke-9, Cemeti Art House (rumah seni yang pernah mendapatkan IAI/Ikatan Arsitek Indonesia Award) karya arsitek Eko Prawoto (satu-satunya arsitek Indonesia yang pernah diundang ke pameran Venice Biennale), sanggar seni serta studio rekaman milik Butet Kartarahardja dan Djaduk karya Eko Prawoto, rumah tinggal Butet karya Eko Prawoto juga, serta rumah Eko Prawoto sendiri, Candi Prambanan dari jaman dinasti Sanjaya dengan rajanya Rakai Pikatan, tempat pemandian putri Kraton Yogyakarta Taman Sari karya arsitek dari Portugis dan melewati Kali Code karya Romomangun yang berhasil mendapatkan penghargaan internasional Aga Khan Award. Sedangkan di Solo kami mengunjungi tempat-tempat seperti sanggar seni budaya Sono Seni milik Sardono W. Kusumo (seniman), guest house tradisional bernama Cakra, kampus UNS, kantor Java Plant di Tawangmangu karya arsitek Andra Matin (sebuah proyek yang saya pernah terlibat namun belum sempat melihat secara langsung) serta rumah karya arsitek Idris Samad dan 3 buah karya seorang kontraktor bernama Paulus.

Eko Prawoto's House design by Eko Prawoto
Di Jakarta atau kota-kota besar lainnya kita sering disuguhi dengan berbagai macam desain dengan beragam style, corak, karakter, tren dan lain sebagainya. Namun terkadang dengan dipesonakannya kita dengan bermacam-macam ragam tersebut, kita seperti terbuai dengan gemerlapnya warna-warni desain yang beragam yang akhirnya membawa kita untuk ikut berlomba meramaikannya. Kadang kita lupa dengan apa yang namanya kontekstualitas. Setelah merasakan pengalaman-pengalaman tadi akhirnya timbul pertanyaan dari benak masing-masing kami, apakah Jakarta atau kota-kota besar lainnya memiliki kontekstualitas? Mungkin kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, Medan masih mempunyai sebuah kontekstualitas walaupun sudah mulai terkikis oleh derasnya arus kapitalisme. Bagaimana dengan Jakarta, apakah Jakarta punya? Dan kontekstualitas Jakarta itu seperti apa sich? Kami yang telah melakukan perjalanan tadi mempunyai kesimpulan bahwa Jakarta hampir “no-context”. Kenapa hampir? Karena di beberapa spot Jakarta, masih terdapat semangat-semangat yang masih mempertahankan kontekstualitas Jakarta sendiri walaupun sudah mulai terdesak dengan gelombang pembangunan yang secara membabi buta menerornya.

Java Plant office design by Andra Matin
Memanfaatkan konteks dalam hal penyesuaian desain terhadap iklim tropis setempat juga dilakukan oleh arsitek-arsitek Eko Prawoto, Paulus, Andra Matin dan Idris Samad pada karya-karyanya. Semua karya mereka untuk ruang bersama tidak memakai penyejuk ruangan (AC), mereka memanfaatkan ventilasi silang di lokasi yang juga banyak memiliki vegetasi yang rimbun yang secara sengaja pula tetap dibiarkan (tidak dibabat habis). Pada karya Eko Prawoto di rumahnya dan rumah Butet serta karya Paulus, desain merekalah yang menyesuaikan peletakkan pohon di site, dan tidak membabat habis pohonnya, bahkan di dalam rumah Eko, pohon tetap dibiarkan sebagai elemen interior yang langsung menembus atap. Idris Samad dan Paulus banyak melakukan pendekatan desain beriklim tropis dengan memanfaatkan atap sebagai pendingin ruang dibawahnya dengan memakai roof garden, atap ditanami rumput yang tinggi-tinggi terlihat pada karya-karyanya dan kantornya sendiri.

Sonoseni Art Studio of Sardono W. Kusumo
Sedangkan di sanggar seni Sono Seni milik Sardono W. Kusumo, saya seperti melihat sebuah karya yang menerapkan konsep dekonstruksi secara tidak sadar. Lokasinya berada di dalam sebuah gang sempit di kota Solo, dan memanfaatkan rumah bekas yang direnovasi secara tidak konvensional. Keunikannya terlihat seperti pada pintu-pintunya termasuk pintu gerbang yang dibuat hanya dengan membongkar dinding dan tidak dirapikan kembali. Kemudian di lokasi juga dibuat ruang-ruang khusus seperti ruang bermeditasi yang sebenarnya berfungsi sebagai ruang latihan vokal. Selain itu juga terdapat 3 buah panggung yang dapat digunakan secara terbalik-balik, panggung kesatu berfungsi sebagai panggung pentas, sedangkan lainnya sebagai tempat duduk penonton, atau bisa sebaliknya. Pentas internasional sering digelar di tempat ini termasuk yang diadakan oleh Erasmus Huis ataupun Japan Foundation.
Tempat pemandian putri keraton Yogya Taman Sari karya seorang arsitek yang berasal dari Portugis juga merupakan karya dengan luas lahan yang cukup besar, pola sirkulasinya hampir menyerupai labirin yang di dalam lokasi tersebut juga terdapat perkampungan penduduk. Sayang karya yang megah terebut ada bagian yang roboh ketika terjadi gempa kemarin, walaupun sedang dilakukan reservasi oleh mahasiswa-mahasiswa UGM. Kami beruntung karena kami mengunjungi tempat tersebut serta tempat-tempat di Yogyakarta lainnya pada hari Jumat, sedangkan ketika gempa hari Sabtu kami sudah berada di Solo, sehingga sempat mendokumentasikannya. Namun kami cukup prihatin dan ikut berduka cita atas kejadian musibah gempa kemarin yang menelan cukup banyak korban.

Sendang Sono by Romomangun
Semua yang kami alami serta rasakan membawa pelajaran yang berharga buat kami semua yang sedang belajar akan sebuah proses kreatif dalam mendesain. Kami berharap referensi-referensi yang terekam dalam memori kita secara intuitif dapat memberikan kekuatan fondasi kami dalam mendesain sebuah karya yang tetap menjunjung nilai kesederhanaan dan kejujuran terhadap konteks dan tidak silau lagi menghadapi desain-desain yang saling berlomba-lomba mengikuti tren dan pasar belaka. Mudah-mudahan tulisan ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.

Sigit (left) & his journey friends waiting for a train in Senen Station, Jakarta
Yogyakarta & Solo, Indonesia 2006 (Traveling) "Nilai Keserdehanaan dan Kejujuran Sebuah Desain":
http://sigitkusumawijaya.multiply.com/photos/album/42Work Description:
Title: "Nilai Keserdehanaan dan Kejujuran Sebuah Desain"
Writer: Sigit Kusumawijaya
Status: Journey reviewYear: 2006